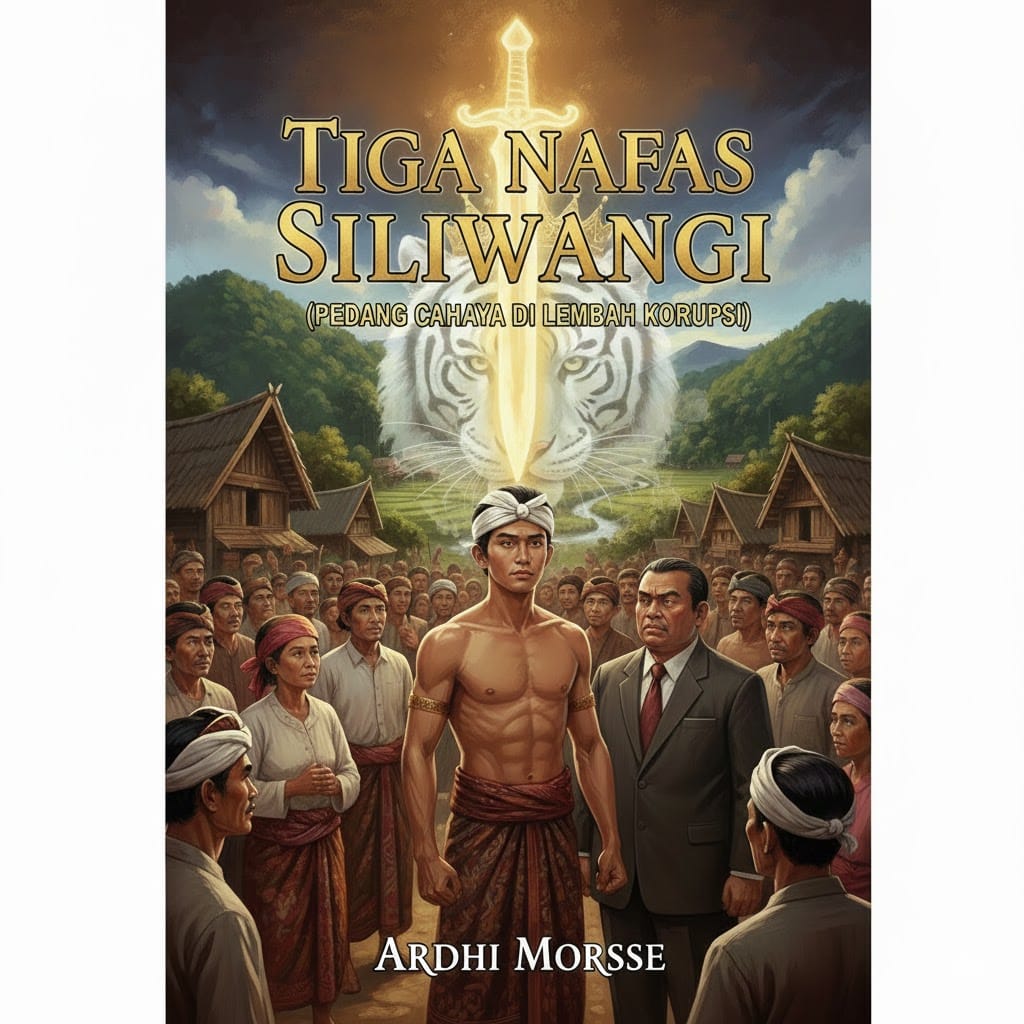KAMPUNG NGALUYU
Kabut turun lebih cepat malam itu, tidak ada suara jangkrik, hanya desir angin dari hutan Larangan yang terdengar seperti bisikan para karuhun yang resah. Kampung Nagaluyu bukan lagi kampung damai yang dulu dibanggakan orang-orang tua.
Di bawah kepemimpinan Kepala Kampung Wangsadra, tanah mulai dijual secara diam-diam kepada para makelar kota, irigasi dialihkan untuk sawah milik pejabat kecamatan, dan pemuda kampung dijadikan tenaga kasar tanpa upah.
Semua dimulai ketika tambang batu giok ditemukan di hulu sungai dan seperti kata karuhun:
“Lamun harta digali, maka iblis bakal dibébaskeun.” (Ketika harta digali, iblis akan ikut terbebas.)
I. Tumbuhnya “Rama” di Tengah Kerusakan
Purwa, pemuda yang selama ini menjaga ladang kecil peninggalan ayahnya, melihat bagaimana retakan moral itu terjadi perlahan.
Namun ia memilih diam, sampai suatu malam ia melihat seorang petani tua “Ki Darmaga” ditarik paksa oleh anak buah Kepala Kampung.
“Bayar pungutan! Sawahmu mengalir dari sungai yang akan jadi milik pemerintah!”
Ki Darmaga hanya menangis. Ia sudah menjual kambing terakhirnya.
Purwa berdiri di depan mereka, “Aya aturan naon? Anjeun teu boga hak!” teriaknya.
Namun pukulan mendarat ke wajahnya. Ia jatuh, Darahpun mengalir. Tapi saat wajahnya menempel tanah, ia mendengar…
bisikan lirih dari bumi Parahyangan, Suara yang lebih tua dari leluhur mana pun.
“Jangan mundur, anak muda. “Rama” lahir dari luka yang ingin disembuhkan.”
Purwa bangkit. Mata para pemukul itu sempat goyah. Ia berkata, dengan darah mengalir dari hidung:
“Rama téh jalma anu nyanghareupan bencana bisi jalma séjén cilaka.”
(Rama adalah orang yang menghadang bencana agar orang lain selamat.)
Ia memeluk Ki Darmaga, melindunginya dari tindakan kecil itu, rakyat mulai melihat secercah harapan. Namun harapan adalah ancaman bagi penguasa korup.
II. Kebijaksanaan yang Terkubur di Lembah Gelap
Setelah kejadian itu, Purwa dicari oleh aparat kampung. Maka ia melarikan diri ke lembah Larangan, menuju gubuk tua tempat tinggal Eyang Mandrajati, resi terakhir yang masih tersisa.
Orang-orang bilang resi itu sudah tidak sepenuhnya hidup. Ia berdiri di ambang dunia manusia dan dunia roh.
Ketika Purwa tiba, Eyang Mandrajati sedang duduk di batu besar, dikelilingi kabut tipis, seperti sedang berbicara dengan mereka yang sudah meninggal, “Eyang… kampung kami hancur. Korupsi mengalir lebih deras dari sungai. Aku ingin melawan… tapi aku takut tersesat.”
Eyang menatapnya. Sorot matanya jernih seperti mata air yang belum disentuh manusia.
“Purwa,” katanya pelan, “Kakuasaan tanpa Resi bakal ngaruksak, tapi kebijaksanaan tanpa kakuatan ngan jadi dongeng kosong.”
(Kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan menghancurkan, tetapi kebijaksanaan tanpa kekuatan hanya menjadi dongeng kosong.)
Malam itu, Eyang mengajarkan Purwa tentang “Tiga Nafas Siliwangi” (ajaran kuno yang pernah diberikan Prabu Siliwangi kepada para pangawinnya),
Nafas Wening: Jernih dalam membaca musuh
“Nu loba sora teu salawasna leres, nu sepi tara hartina salah.”
Nafas Kawani: Berani pada tempatnya
“Kawani lain ngalawan sadayana, tapi nangtung di tempat nu bener.”
Nafas Wibawa: Menundukkan tanpa mengancam
“Rasa hormat henteu dipénta, tapi ditandur.”
Dalam hening lembah itu, Purwa merasa hatinya dibersihkan. Ia belajar bahwa seorang Resi bukan sekadar bijak, ia menjadi cermin bagi pemimpin. Namun resi itu memberi peringatan keras:
“Jalanmu bakal gelap. Sababaraha jalma bakal ninggalkeun anjeun. Sababaraha bakal ngadoleskeun Anjeun. Tapi ingat: ksatria Siliwangi moal éléh ku kamelang, ngan bisa éléh ku hawa nafsuna sorangan.”
Kabut di sekitar mereka bergetar. Seolah para karuhun menyetujui.
III. Ketegasan yang Harus Dipilih
Sepulang dari lembah Larangan, Purwa menemukan kampungnya berubah makin parah. Buldozer sudah bersiap meratakan ladang untuk proyek tambang. Orang-orang desa dipaksa tanda tangan surat pelepasan tanah. Polisi desa ikut mengamankan operasional makelar.
Kepala Kampung Wangsadra berdiri di tengah kerumunan, wajahnya sinis.
“Purwa,” katanya, “kau kembali? Bagus. Sekarang tunduklah, atau kampung ini akan kami anggap melawan pemerintah.”
Purwa melangkah maju, “Abah Wangsadra, tanah ini bukan warisan pemerintah. Ini warisan karuhun kami.”
Ia menatap semua warga lalu berkata lantang, “Ratu téh lain soal tahta, tapi soal kasatiaan ngajaga rahayatna.”
(Ratu bukan soal takhta, tetapi soal kesetiaan menjaga rakyatnya.)
Orang-orang mulai semangat. Namun Kepala Kampung mengangkat tangan, memberi kode. Para preman datang membawa parang. Suasana menjadi gelap. Angin berhenti. Hutan Larangan seakan menahan napas.
Purwa berdiri di depan warga, seperti batu karang menghadang badai, “Lamun hirup kudu ragrag, ragragna kudu bermakna.”
(Jika hidup harus gugur, maka gugurlah dengan makna.)
Para preman menyerbu.
Tapi malam itu, terjadi sesuatu yang kelak disebut orang-orang sebagai “Wanci Karuhun Ngagungkeun Tanah”—(Waktu Leluhur Menjaga Tanah.)
Angin berputar, kabut turun menyeruak, dan suara gamelan samar terdengar dari hutan. Preman-preman itu terjatuh satu per satu, bukan karena pukulan, tapi karena ketakutan, seolah ada sosok-sosok tinggi yang berjalan di belakang Purwa, tak terlihat namun terasa.
Wangsadra lari terbirit-birit.
Tambang batal.
Buldozer ditarik mundur.
Warga bersujud syukur.
Purwa berdiri tegak, tapi wajahnya pucat. Ia tahu apa yang datang malam itu bukan kekuatan dirinya sendiri.
Ia berbisik, “Hatur nuhun, para karuhun… tapi ini baru awal.”
IV. Titah Terakhir: Cahaya yang Menjadi Pedang
Beberapa hari kemudian, warga menobatkan Purwa sebagai pemimpin adat baru. Bukan raja, bukan kepala kampung, tetapi “Ratu Lembur” Pemangku Keadilan Kampung.
Di depan balai adat, Purwa berkata, “Siliwangi ngajarkeun: ‘Sing jadi ratu pikeun rasa, jadi rama pikeun nu lemah, jadi resi pikeun diri sorangan.’”
(Siliwangi mengajarkan: Jadilah ratu untuk keadilan, rama untuk yang lemah, dan resi untuk dirimu sendiri.)
Ia memimpin pembongkaran pos pungli, membuka kembali irigasi untuk rakyat kecil, dan memperbaiki hubungan antarwarga.
Namun korupsi tidak hilang seketika. Politisi dari kabupaten mulai memperhatikannya. Konflik baru terasa seperti menunggu di balik bukit.
Purwa menyadari, perjuangannya baru dimulai dan setiap kali ia berdiri di bukit Nagaluyu, ia mendengar lagi bisikan itu, “Ksatria Siliwangi hirup lain pikeun kamulyaan diri, tapi pikeun cahaya anu moal pernah eureun dijarkeun.”
(Ksatria Siliwangi hidup bukan untuk kemuliaan diri, tetapi untuk cahaya yang tidak pernah berhenti diajarkan.)
Dan begitulah Nagaluyu menemukan pemimpinnya, bukan dari darah bangsawan, bukan dari suku pertama, tetapi dari seseorang yang berani menjadi Rama, belajar menjadi Resi, dan terpaksa menjadi Ratu.
KONFLIK DENGAN PEMIMPIN KABUPATEN
Kabut Parahyangan sore itu tampak lebih pekat dari biasanya. Orang-orang tua kampung mengatakan, “Lamun kabut siga kieu, tandana aya anu datang teu jeung niat hadé.”
Mereka benar.
Sebuah rombongan mobil hitam menggilas jalan tanah menuju Kampung Nagaluyu. Di dalamnya, duduk seorang lelaki berjas tebal, dengan cincin emas besar di jari: Bupati Darmawangsa, Ia politisi kabupaten yang selama ini dikenal lihai dalam permainan kekuasaan.
Ia turun, menatap kampung dengan senyum kaku. Tatapan kaku matanya… tajam seperti pisau.
Tekanan dari Kabupaten
Di balai adat, ia duduk berhadapan dengan Purwa, para tetua, dan warga.
“Saudara Purwa,” katanya merdu, “kabupaten ingin membangun proyek GeoPark di tanah ligan kampung ini. Wisata, Investasi dan Kemajuan.”
Purwa merasakan hawa dingin. Ia tahu: proyek itu hanyalah pintu masuk untuk mengambil batu, kayu, dan tanah adat.
Purwa menarik napas, “Tanah karuhun mah lain dagangan… éta amanah.”
(Tanah leluhur bukanlah barang jualan… itu amanah.)
Bupati tersenyum, seolah sudah menduganya, “Bagaimana kalau kabupaten memberi kompensasi?”
Amplop tebal diletakkan di meja, suasana pertemuan menjadi ramai, Wargapun mulai gelisah.
Purwa berdiri, “Ratu anu sajati moal nyokot nu teu pantes sanajan disodor-sodorkeun ku emas.”
(Pemimpin sejati tak mengambil yang tak pantas, meski emas disodorkan padanya.)
Suasana ruang di balai pertemuan memanas dan menegang.
Bupati merapikan jasnya. “Saya akan kembali lagi, Pikir baik-baik, Dunia ini bukan dunia dongeng dan Semua orang… punya harga.”
Ia pergi meninggalkan balai adat dengan tatapan gelap yang menjanjikan badai.
Politik Kotor Mulai Menjalar
Hari-hari berikutnya suasana kampung mulai berubah, fitnah-fitnah mulai tersebar di kabupaten,
“Purwa radikal.”
“Purwa anti pembangunan.”
“Purwa punya kepentingan pribadi.”
Surat dari kabupatenpun datang, Purwa dipanggil untuk diperiksa karena “melawan program pemerintah”.
Beberapa warga yang lemah iman mulai goyah, mereka ada yang diam-diam menerima uang dari utusan bupati.
Purwa melihat perubahan dan kondisi warga yang mulai menerima uang dari penyusup atas printah bupati dengan mata yang mulai letih.
Pada suatu malam, ia duduk sendirian di bawah pohon Kihiyang, pohon keramat peninggalan karuhun.Angin lirih berbisik di telinganya. Ayunan daun terdengar seperti suara dari masa lalu.
Tiba-tiba, muncul bayang samar. Itu Sang Pamuja Jagat, salah satu karuhun kampung, wajahnya tertutup kabut, suaranya menyerupai desir sungai.
“Anaking Purwa…”
“Jalan “Rama, Resi, Ratu” yang kau tempuh tidak berhenti di sini.”
Purwa pun menunduk, air matanya menetes.
“Karuhun… abdi parantos ngantosan kakuatan. Dunia politik ieu kacida kotorna.”
Sang Karuhun menjawab, “Kakuatan anu paling bahaya téh lain musuh di luar, tapi ragu dina jero haté.”
(Kekuatan paling berbahaya bukan musuh di luar, tetapi keraguan di dalam hati.)
Lalu secara perlahan bayang di hadapan purwa itu hilang dan malam terasa lebih gelap.
Saat Pengkhianatan Terjadi
Esok harinya, kabar buruk datang, Salah satu pemuda kampung, ‘Gilar’ yang dahulu pernah Purwa tuntun dalam lingkar Resi, tertangkap tangan warga sedang bersama rombongan kabupaten memasang patok proyek.
Purwa sangat kecewa dengan peristiwa itu, tapi ia mendekati Gilar dengan tenang.
“Gilar, kunaon?”
Pemuda itu menunduk lemah tidak berani menatap wajah purwa,
“Abdi… gaduh kahayang hirup leuwih hadé. Bupati masihan abdi jabatan… jeung duit.”
Purwa memejamkan mata, Ia belajar menerima luka ini.
“Nu ngajadikeun ratu gedé téh lain jumlah anu nurut, tapi sabaraha anu bisa dirangkul sanajan nganyeri.”
(Yang membuat pemimpin besar bukan berapa banyak yang tunduk, tetapi berapa banyak yang bisa dirangkul meski menyakitkan.)
Kejadian pemasangan patok-patok itu melupakan permasalahan awal.
Selanjutnya, Di balai desa, surat resmi tiba, menyatakan bahwa Kabupaten akan memulai proyek paksa dan Kampung tidak punya hak menolak, Surat Resmi kabupaten Dibubuhi stempel merah darah.
Hari itu, Purwa memanggil seluruh warga, Ia berdiri di bawah matahari yang berwarna tembaga, seolah langit pun menahan napas,
“Bupati Darmawangsa mengira urang bisa dibeli,” katanya.
“Padahal urang gaduh anu teu bisa dibeli: harga diri karuhun.”
Kemudian, menatap warga satu per satu,
“Ratu anu sajati lain nu ngancam, tapi nu ngajaga.”
(Pemimpin sejati bukan yang mengancam, tetapi yang melindungi.)
Orang-orang mulai berdiri dari tempat duduknya, Mata mereka berubah menjadi kobaran kecil.
Purwa melanjutkan, “Upami urang teu ngajaga tanah ieu ayeuna… urang bakal leungit diri urang sorangan.”
(Jika kita tidak menjaga tanah ini sekarang… kita akan kehilangan diri kita sendiri.)
Dan pada hari itu, seluruh kampung menyalakan obor di batas tanah adat. Seperti lautan cahaya yang menolak dilahap kegelapan.
Benturan Dengan Kekuasaan
Rombongan bupati membawa kendaraan kembali datang, kali ini bersama aparat.
Sang Bupati turun bersama rombongan , wajahnya terlihat gurat kemerahan.
“Kalian menghalangi pembangunan! Ini tindakan melawan negara!” Teriaknya.
Purwa pun melangkah maju, ditemani para tetua kampung.
Ia menatap bupati tanpa gentar sedikit pun, “Negara anu leres bakal ngajagi rahayat, lain ngancurkeunana.”
“Kakuasaan tanpa nurani mah ibarat harimau kelaparan: bisa dahar saha wae, kaasup nu miara.”
(Kekuasaan tanpa nurani adalah harimau kelaparan: bisa memakan siapa saja—bahkan yang memeliharanya.)
Para aparat yang masuk dalam rombongan bupati terlihat bimbang, tidak ada yang berani memulai kekerasan ketika ratusan warga berdiri diam, tanpa senjata, namun dengan tatapan yang tak bisa dibeli.
Bupati diam dan terpojok, akhirnya mundur dengan geram. Ia tahu bahwa kampung ini tidak mudah tunduk. Tapi ia tidak akan berhenti.
Bayang-bayang politik dan kekuasaan rakus selalu punya cara lebih gelap.
Malam itu, Purwa kembali ke pohon Kihiyang. Ia menyalakan dupa, memohon petunjuk.
Angin bergerak aneh. Suara-suara halus terdengar dari dalam batang pohon. Seolah karuhun sedang berunding, memberi jalan atau memberi peringatan.
Purwa berbisik, “Abdi moal mundur… sanajan jalan ieu bakal nyieun getih ngocor di taneuh karuhun.”
Di kejauhan, suara anjing menggonggong, menandakan ada bahaya yang bergerak di perjalanan. Konflik antara pemimpin kampung dan politisi kabupaten kini berubah menjadi perang jiwa, perang kepentingan, dan perang nurani.
Yang gelap belum selesai. Yang mistik belum sepenuhnya bangkit.
SABOTASE, KORUPSI, DAN KEBANGKITAN ROH SILIWANGI
Kabupaten itu tampak biasa di siang hari: rapat DPRD, dengar pendapat, baliho-baliho politik yang basah oleh hujan. Tapi di balik itu semua, aliran uang haram berputar seperti sungai hitam yang tak pernah kering dan Purwa seorang pemuda dari kampung kecil tidak menyadari bahwa kini ia berdiri tepat di tengah arus itu.
Di Nagaluyu, dua minggu setelah Purwa menolak proyek Ardalaksana, hal-hal aneh mulai terjadi.
Awalnya, irigasi sawah tersumbat, warga menyalahkan alam, sampai ditemukan karung-karung plastik di dalam pintu air, karung itu sengaja dimasukkan malam-malam.
Kemudian kandang sapi milik seorang petani tiba-tiba terbakar, padahal malam itu hujan deras. Lalu sumur-sumur mengeluarkan bau logam, membuat air tak layak minum.
Abah Wiradipa menggeleng lirih, “Ini mah sabotase, Purwa… ini mah tangan jahat.”
Purwa mengepalkan tangan, “Lamun dahareun diserang, lembur jadi leuleus. Ieu usaha pikeun mecah urang.”
(Jika makanan disabotase, kampung menjadi lemah. Ini strategi untuk memecah kita.)
Warga mulai resah, Beberapa warga bahkan berkata, “Mungkin kita pasrah saja. Tanah itu biar diambil. Yang penting sarana hidup tidak diganggu.”
Purwa tahu… ini yang diinginkan musuh; ketakutan, bukan perang.
Malam itu ia naik ke bukit pasarean karuhun, Ia duduk diam di bawah pohon besar, mengalunkan doa lama yang diajarkan Eyang Mandrajati.
Dan angin tiba-tiba berubah.
Daun-daun bergetar.
Tanah seperti berdenyut.
Seolah ada yang bangun dari tidur panjang.
Sementara itu di kabupaten, rapat internal berlangsung di sebuah ruangan tertutup pendapa.
Ada Raden Ardalaksana, dua anggota DPRD serta Ada kepala dinas dan ada seorang pengusaha tambang asing berwajah dingin.
Di meja mereka, bukan hanya peta Nagaluyu, tapi juga koper hitam yang berisi uang mengalir dari proyek-proyek siluman.
“Apa pun yang terjadi,” kata Ardalaksana sambil memukulkan jari ke meja, “Nagaluyu harus kosong dalam tiga minggu. Kita rapikan dokumennya sebagai ‘relokasi bencana alam’.”
Salah satu anggota DPRD bertanya ragu, “Kalau ada wartawan?”
Ardalaksana tersenyum licin, “Kita punya humas, Kita punya polisi dan kita punya uang.”
Ia menambahkan, “Kalau kampung itu keras kepala… hancurkan, Banjir bandang bisa direkayasa dan Kebakaran bisa dipicu. Dunia ini bukan dunia orang bersih.”
Secara bersama Mereka tertawa lirih, Tawa orang-orang yang merasa kekuasaan ada di tangan mereka.
Di sudut ruangan, asap dupa beraroma aneh mengepul, Pengusaha asing itu membakar sesuatu dan berbisik dalam bahasa yang tidak dikenali dan ketika asap menyentuh peta Nagaluyu, warnanya menghitam.
Teror Malam: Bayangan Hitam di Balik Pintu
Malam itu, Purwa meronda bersama para pemuda kampung. Angin dingin turun tiba-tiba, membawa bau amis, dan Dari kejauhan terlihat sosok-sosok berpakaian hitam merayap di antara pohon.
Terlalu banyak untuk disebut maling, terlalu terlatih untuk disebut preman biasa. Tanpa suara, mereka menyelipkan kain bensin di beberapa rumah. Satu percikan saja… kampung terbakar.
Purwa berlari dan berteriak, “Warga! Ka luar! Aya anu rék ngaduruk lembur!”
Api pertama menyala.
Warga berhamburan.
Suara jeritan bersahutan.
Tapi tiba-tiba… angin berhenti, Betul-betul berhenti. Api yang berkobar membeku seperti lilin yang dilindungi kaca. Pemuda hitam yang menyalakan api mendadak menjerit, terpelanting seperti dipukul sesuatu yang tak terlihat.
Warga membisu, Purwa merasakan tengkuknya merinding, Dari balik kabut yang keluar dari hutan Cadas Sangiang, muncul sesuatu…
Bukan manusia.
Bukan pula hewan.
Siluet besar.
Berpunggung seperti harimau.
Bermata seperti bara yang dingin.
Langkahnya berat tapi hening, dan ketika ia menatap para penyerang itu, para preman kabupaten itu langsung lari pontang-panting seperti anak kecil melihat kematian.
Warga gemetar.
Purwa menunduk perlahan.
Ia tahu sosok apa itu.
Ia tahu nama yang sejak kecil hanya disebut dengan hormat, bukan dengan suara keras.
“Roh Siliwangi…” Gumam Abah Wiradipa sambil bergetar.
“Kekuatan karuhun nu ngajaga tanah ieu.” Kekuatan leluhur yang menjaga tanah ini.
Dan sosok itu… Menatap Purwa. Ia tidak marah, tidak juga ramah.. Hanya mengakui.
Seolah berkata, “Anaking… ayeuna giliran anjeun nangtung.” (Nak… sekarang giliranmu berdiri.)
Sosok itu lalu menghilang ke balik kabut dan pepohonan, dan Malam Kembali damai, wargapun kembali ke rumah.
Pagi itu kampung Nagaluyu berkumpul, mereka melihat bekas sabotase, bekas api, bekas ancaman.
Tapi mereka juga melihat, tidak satu pun rumah yang hancur dadatidak satu pun warga yang terluka, Seolah ada tameng besar yang melindungi kampung dan warga kini memandang Purwa bukan sebagai pemuda biasa, tapi sebagai pemimpin yang mendapat restu alam.
Abah Wiradipa berkata lantang, “Upama politisi boga duit, urang boga karuhun.”
(Jika politisi memiliki uang, kita memiliki leluhur.)
Warga semuanya yang bersorak. Purwa menatap bukit berkabut itu dan berbisik, “Siliwangi, tuntun abdi… Perang ieu tacan réngsé.”
Ia tahu kebangkitan roh leluhur bukan akhir… Ini baru awal dari amukan besar, karena Ardalaksana akan marah. Kabupaten akan mengerahkan kekuatan penuh dan korupsi yang berbau darah itu tidak akan berhenti hanya karena satu kampung kecil melawan.
Operasi Hitam Kabupatenpun, dan Akhir dari Tanah yang Dijaga Langit
Malam sebelum semuanya pecah, kabupaten seperti bersiap untuk perang, tidak dengan meriam, tidak dengan tank. Mereka siap dengan cara yang lebih halus dan lebih kejam.
Operasi ini mereka sebut, “Operasi Padaringan” operasi untuk mengeringkan kampung, memeras habis semangat hidupnya, hingga warga menyerah tanpa mereka perlu menembakkan satu peluru pun.
Bagi mereka, Nagaluyu hanyalah tanah kecil tanpa suara, tapi mereka lupa satu hal:Tanah yang dijaga leluhur bukan tanah kosong.
Esok paginya, kabupaten menggelar konferensi pers besar, Wartawan-wartawan dari kota diundang. Mereka duduk sambil membuka laptop, kamera terarah.
Raden Ardalaksana masuk dengan wajah tenang dan senyum palsu yang sudah terlatih.
Ia berkata, “Kami mendapati indikasi bahwa kampung Nagaluyu kini menjadi tempat persembunyian kelompok radikal yang menolak pembangunan.”
Di layar besar, muncullah foto Purwa yang diambil diam-diam dengan cahaya redup sehingga tampak mencurigakan.
Ardalaksana melanjutkan, “Purwa ini pemuda yang terindikasi menerima dana asing untuk menghambat investasi nasional.”
Tentu saja itu bohong, Tapi media menulisnya cepat dan Berita menyebar lebih cepat dari doa.
Di Nagaluyu, warga mulai ketakutan, Ada yang bertanya lirih, “Apa Purwa benar begitu?”
Yang lain menjawab, “Mustahil… tapi pemerintah mana pernah salah?”
Dan di tengah kegaduhan itu, Purwa hanya berkata pelan, “Ratu anu bener bakal difitnah heula, tempatna di adu heula, najan anjeunna suci.”
(Pemimpin yang benar akan difitnah dulu, dilukai dulu, meski ia tak bersalah.)
Ia menatap kampungnya, bukan dengan marah—tapi dengan keteguhan.
Sore harinya, datanglah rombongan konvoi polisi memasuki kampung, Sirene meraung dadamobil hitam berbaris.
Komandan polisi turun dan membacakan surat, “Sesuaikan dengan aturan kabupaten, wilayah ini akan disegel karena diduga mengancam keamanan investasi.”
Warga pun beramai-ramai menolak dan berteriak, “Ini tanah kami! Pasarean karuhun kami!”
Tapi polisi tidak peduli, Mereka dibayar untuk mematikan suara rakyat.
Purwa berdiri di depan barisan polisi, “Jangan sentuh pasarean, di sana tinggal roh karuhun.”
Komandan tertawa sinis, “Roh? Kau pikir roh bisa menghalangi penetapan pemerintah?”
Lalu ia memberi aba-aba, “Bongkar pagar! Masuk semua!”
Polisi mulai menebang pohon,
Menggali tanah,
Mengangkat batu-batu leluhur,
Dan membawa alat berat memasuki batas suci pasarean.
Tiba-tiba Tanah itu bergetar,
Angin berhenti,
Kabut turun cepat, tidak wajar.
Eyang Mandrajati muncul sambil membawa tongkat tua.
“Tahan! Tahan! Kami sudah memperingatkan!”
Tapi tak ada yang mendengar, Kecuali… yang ada di balik kabut.
Ketika alat berat menyentuh tanah pasarean, terjadilah sesuatu yang membuat langit terbelah.
Suara menggelegar datang dari bukit, Bukan suara manusia, Bukan pula suara hewan, Seperti raungan harimau bercampur dengan suara badai.
Tiba-tiba pepohonan di sekitar pasarean bergerak serempak, Akar-akar tanah keluar seperti tali yang membelit dan Angin dingin menyapu kampung, membuat seluruh polisi mundur ketakutan.
Dan dari balik kabut itu…Sosok besar muncul, Bukan Cuma bayangan seperti sebelumnya.
Kini jelas,
Harimau besar berselimut cahaya emas kebiruan, matanya bagaikan bara redup, tubuhnya setengah manusia, setengah raksasa. Itu bukan jin apalagi hantu.
Itu Roh Siliwangi dalam bentuk perlindungan penuh. Polisi berhamburan, Alat berat terangkat sendiri dan terlempar ke sungai dan Pohon-pohon berdiri kembali seperti mengusir penyusup.
Raden Ardalaksana yang datang kemudian, melihat itu dengan wajah pucat.
Ia berteriak, “Apa-apaan ini!? Ini gaib kampungan! Saya panggil tentara! Saya panggil semuanya!”
Siliwangi menatapnya, Satu tatapan itu membuat lututnya lemas.
Purwa maju ke depan, Ia memegang tongkat yang diberikan Eyang Mandrajati, “Siliwangi… cukup. Biarkan aku yang menyelesaikan ini.”
Sosok itu berhenti, perlahan Menunduk dan berangsur menghilang seperti kabut kembali ke langit.
Kini tinggal Purwa…dan manusia-manusia tamak yang kini ketakutan.
Kejadian itu tidak dapat disembunyikan, semua warga merekam dan para wartawan lari panik. Video-video naik ke media. Dunia menonton, Kabupaten geger dan pemerintah Pusat turun tangan melakukan Investigasi besar. Kasus korupsi mencuat: dokumen palsu, proyek ilegal, aliran uang gelap, transaksi tambang ilegal.
Raden Ardalaksana ditangkap serta Beberapa pejabat ikut terseret dan Pendapa Kabupaten menjadi simbol runtuhnya kekuasaan gelap.
Desa Nagaluyu akhirnya menjadi kawasan adat yang dilindungi. Pasarean karuhun tak boleh disentuh tanpa adat, tanah digaris merah dan tak boleh diperjualbelikan. Warga kembali hidup dengan damai.
Purwa tidak menjadi kepala kampung. Ia menolak ketika akan di jadikan pemimpin desa,
Ia hanya berkata, “Abdi mah cukup jadi panyala lampu. Rakyat nu boga cahaya.”
(Aku cukup menjadi penyala lampu. Rakyatlah pemilik cahaya.)
Namun semua orang tahu…
Pemuda itulah pemimpin sejati.
EPILOG: CAHAYA YANG TIDAK PERNAH PADAM
Suatu pagi, Purwa naik kembali ke bukit pasarean. Ia membawa bunga, meletakkannya pelan.
“Karuhun… hatur nuhun. Hatur nuhun parantos ngajaga lembur.”
Angin bertiup lembut, Seperti tangan tua menepuk bangajagal
Dari kejauhan, samar terdengar suara, “Lamun bumi dijaga ku anu ikhlas, langit bakal nurunkeun wibawa.”
(Jika bumi dijaga oleh yang ikhlas, langit pun akan menurunkan wibawa.)
Dan di langit Parahyangan, ada kilatan cahaya emas yang seperti membentuk wajah harimau.
Siliwangi tidak pergi, dan Tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu…
Hingga suatu hari, manusia kembali lupa siapa leluhurnya.
ARDHI MORSSE, TANGERANG 28 NOVEMBER 2025