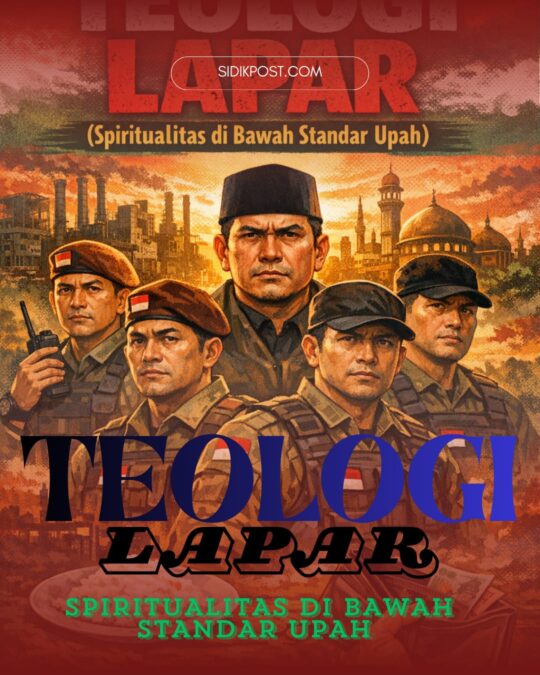Prolog
Kisah cerita ini lahir dari perjumpaan antara iman manusia dan kenyataan kehidupan. Antara azan Maghrib di hari pertama bulan ramadhan dan slip gaji yang memprihatinkan. Antara jeritan hati dan doa yang lirih serta angka yang jauh dari cenmukupi. Di Wilayah kota madya yang menyebut dirinya kota industri karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang besar serta Nilai maksimal daribUpah Minimum Kota yang ditetapkan secara resmi, ada ironi yang sunyi, Mereka aparatur negara yang bertugas di lapangan, tapi hidup jauh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah daerahnya sendiri.
“Teologi Lapar” bukan sekadar cerita tentang pegawai ASN lapangan golongan rendah yang kekurangan materi. Ia merupakan refleksi tentang bagaimana spiritualitas diuji di tengah ketimpangan dan ketidakadilan struktural. Bagaimana iman dipertanyakan ketika kebijakan tidak berpihak. Bagaimana sabar dibenturkan dengan ketidakkeadilan Dan bagaimana aparat yang diminta menjaga ketertiban, ketentraman justru bergulat dengan kegelisahan batin tentang martabat dan pemenuhan nafkah.
Bulan Suci Ramadhan selalu dipahami sebagai bulan menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi dalam kisah ini, lapar bukan hanya ritual ibadah, Ia menjadi simbol dari realitas kehidupan sosial mulai dari ketika gaji berada di bawah standar hidup minimum dan ketika tuntutan profesionalisme tinggi tetapi kesejahteraan tertinggal, serta ketika keadilan lebih sering menjadi slogan daripada kebijakan yang nyata.
Melalui tokoh-tokoh seperti Bhumi, Cak IIP, Kang Ibay, Satria Perkasa, dan rekan-rekannya, kisah cerita ini berusaha menelusuri satu pertanyaan mendasar: apakah kesalehan bisa berdiri tegak di tengah ketidakadilan dalam struktural pemerintah daerah? Ataukah justru kesalehan itu sendiri menuntut keberanian untuk bersuara keras?
Sejarah pemikiran Islam mengajarkan bahwa agama tidak pernah netral terhadap kezaliman apalagi yang di lakukan oleh seorang pemimpin. Para ulama besar dari Imam Al-Ghazali hingga Ibnu Khaldun berpendapat bahwa, “keadilan merupakan fondasi kekuasaan. Ketika keadilan retak, legitimasi pun perlahan terkikis. Maka spiritualitas tidak boleh direduksi menjadi kesabaran pasif, melainkan harus menjadi kesadaran moral yang aktif.”
Kisah cerita ini tidak ditulis untuk menumbuhkan kebencian terhadap individu atau institusi tertentu. Ia ditulis sebagai pandangan agar kita berani melihat wajah kita sendiri dalam sistem yang kita jalankan. Ia menjadi undangan untuk berpikir ulang tentang prioritas anggaran, tentang keberanian kepemimpinan dan tentang makna amanah dalam menjalankan roda pemerintahan serta kekuasaan.
Karena pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah kota bukan hanya pada gedung-gedung yang menjulang atau angka investasi yang meningkat, tetapi pada sejauh mana ia menjaga martabat mmelalui pemenuhan kebutuhan hidup serta mensejahterakan manusia yang bekerja untuknya. Dalam konteks inilah, “Teologi Lapar” menjadi penting untuk mengingatkan bahwa iman tanpa keadilan hanya menjadi retorika, dan kebijakan tanpa empati hanya kekosongan.
Semoga kisah cerita ini menjadi ruang perenungan dan evaluasi Bagi aparat yang sedang berjuang menjaga integritasnya dan Bagi pemimpin yang memegang kendali kebijakan, serta bagi kita semua yang percaya bahwa spiritualitas sejati tidak pernah berdiri di luar realitas sosial, melainkan tumbuh dan diuji di dalamnya.
Bulan Ramadhan mengajarkan kita untuk menahan lapar. Tetapi ketidakadilan mengajarkan kita untuk tidak membiarkan lapar itu menjadi takdir yang dipaksakan.
Dilema Hari Pertama Bulan Ramadhan
Langit hari pertama Ramadhan di Kota Industri Terlihat mendung. Matahari tidak menampakkan sinarnya yang terang hanya menyisakan lelah di wajah para pegawai aparat lapangan yang sejak pagi melaksanakan patroli ke wilayah-wilayah dan mengatur ketertiban pasar, pedagang serta arus kendaraan menjelang waktu berbuka.
Bhumi lalu melepas topinya, walaupun tidak terlalu panas namun padatnya kegiatan membuat Keringat membasahi kerah seragam PDL coklatnya.
“Bulan Ramadhan selalu mengajarkan sabar tapi tahun ini mengajarkan cara bertahan,” katanya pelan, “tapi sabar dan terus bertahan tidak pernah berarti membiarkan kezaliman semakin merajalela.”
Di sampingnya Cak IIP sedang berdiri dan memeriksa pesan di ponsel, Istrinya mengirim video anaknya yang sedang berbibarat, “Ayah, nanti kalau buka puasa beliin ayam goreng ya?”
Cak IIP melihat video sambil tersenyum getir, “Kemarin mereka berbicara cuma minta es buah, Hari ini minta ayam ayam goreng, kalau Tahun lalu masih bisa tapi untuk Sekarang…” Ia terdiam, sambil menahan nafas.
Kang Ibay, yang bertubuh gemuk dengan topi hitam dan jaket putih berjalan mendekati dan menepuk bahunya sambil berkata, “Saat ini, Server rumah tangga kita semua sedang overload, Cak, karena Input kebutuhan terus naik tapi, bandwidth gaji tetap bahkan berkurang banyak.”
Sedangkan Defan dan Erdan masih sendiri dan masih perjaka, tapi tidak banyak bicara. karena mereka pun tidak lepas dari pesan keluarga.
“Ibu bilang, kalau bisa tambahin sedikit untuk beli kue, sirup dan kurma,” ujar Erdan lirih.
“Adik saya bilang, Ramadhan tahun ini jangan cuma janji,” tambah Defan.
Tidak terlalu jauh dari mereka, Komandan Satria Perkasa sedang duduk sendirian. Wajahnya tegas, tapi sorot matanya retak oleh kegelisahan sekaligus kebimbangan.
Ia membaca pesan handphone, karena baru saja menerima pesan dari istrinya, “Bang, anak-anak berharap buka puasa pertama lengkap seperti tahun lalu, tidak perlu mewah dan Cukup sederhana saja.”
Satria masih terus menatap layar handphonenya, lalu berucap lirih, “Bagaimana mungkin aku memimpin pasukan, jika di rumah aku tidak mampu memberikan nafkah yang cukup?”
Bhumi lalu berjalan dan mendekat sambil berkata, “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka…” (QS. Hud: 113), ucapnya pelan.
Lalu Satria menatapnya, “Kau mau bilang aku termasuk pemimpin zalim?”
Bhumi pun menggeleng, “Tidak, Komandan. Tapi sistem pemerintah kita yang membiarkan aparatnya hidup di bawah standar hidup minimum, itu yang namanya kezaliman struktural.”
Angin sore berembus membawa aroma masakan dari warung sebelah.
Lalu Satria memejamkan mata, “Aku diapit dua dunia bhumi, Dari atas, ada perintah dan target kegiatan dan Dari bawah, ada keluarga dan anak buah, Kalau aku bicara keras terhadap kezaliman ini, aku dianggap tidak loyal. Kalau diam, aku mengkhianati hati.”
Cak IIP menyela lirih, “Dalam dunia politik, Komandan, saat ini banyak orang lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan nurani.”
Azan Maghrib pun menggema. Mereka berbuka Puasa hari pertama dengan air putih dan gorengan yang di beli ketika patroli dan dibagi rata.
Bhumi kembali berkata pelan, “Imam Al-Ghazali pernah menulis, kekuasaan tanpa keadilan adalah kehancuran yang tertunda.”
Kang Ibay Pun tersenyum pahit, “Berarti kita sedang hidup di masa pending itu.”
Mamat menatap langit yang menggelap, “Puasa mengajarkan kita lapar agar paham derita orang miskin, Tapi bagaimana kalau yang lapar justru aparatnya sendiri?”
Defan Pun menghela napas sambil berkata, “Kita disuruh menjaga ketertiban, Akan tetapi ketertiban apa yang lahir dari ketimpangan dan ketidakadilan?”
Erdan menambahkan, “Pimpinan kita saat ini seperti buta, tuli, dan bisu. Data ada, Anggaran ada, Tapi keberanian Tidak ada.”
Kata Satir di Bawah Baleho
Di seberang jalan, baleho besar dan memajang wajah pimpinan kota dengan tulisan, “KOTA INDUSTRI, RAKYAT SEJAHTERA.”
Lalu Kang Ibay menunjuknya sambil berkata, “Sejahtera itu kata kerja atau kata hias atau hanya slogan tanpa makna?”
Cak IIP pun menjawab, “Kadang ia hanya slogan yang dicetak besar agar menutupi angka kecil yang menyengsarakan dan membuat penderitaan.”
Satria pun berdiri, “Jangan terlalu keras bicara, karena Kita aparat negara.”
Bhumi menatap komandannya lurus, “Justru karena kita aparat, komandan, kita wajib menjaga dan mewujudkan keadilan. Nabi Muhammad bersabda, ‘Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.’”
Suasan menjadi Hening….
Lampu merah menyala dan Kendaraan-kendaraan berhenti, Seperti kota yang sejenak terdiam. Malam kedua Ramadhan semakin dekat.
Kemudian Satria berbicara lirih, “Aku ingin anak-anak berbuka dengan wajah bahagia, Tapi aku juga ingin pasukanku tidak merasa ditinggalkan apalagi dalam keadaan yang penuh kebimbangan.”
Bhumi kembali menjawab, “Ikhlas itu bukan berarti membiarkan diri kita ditindas, tapi Ikhlas adalah tetap Bergerak dan berjuang tanpa membenci.”
Erdan pun menambahkan, “Kita kritik kebijakan yang tidak Adil bukan karena benci pemerintah. Tapi Kita kritik karena cinta terhadap kota ini.”
Defan tersenyum tipis, “Puasa memang mengajarkan kita menahan amarah, Tapi bukan menahan suara melihat ketidakadilan di depan mata.”
Solusi di antara Tadarus dan Patroli
Mereka terus berdiskusi sebelum kegiatan patroli kembali di mulai dan Di antara tadarus dan patroli malam, mereka mulai merumuskan langkah untuk memberikan peringatan kepada para pemilik kebijakan:
- Mendesak Pemimpin Kota madya Melaksanakan transparansi anggaran secara kolektif.
- Mengusulkan kepada pemilik kebijakan Melaksanakan penyesuaian TPP bertahap agar minimal setara UMK.
- Membuka ruang dialog publik yang terbuka dan jujur.
- Mengingatkan Pemimpin kota madya bahwa kekuasaan melupakan amanah, bukan fasilitas.
Satria mengangguk perlahan, “Mungkin aku tidak bisa melawan dengan teriakan dan demonstrasi,” katanya, “tapi aku bisa memulai dengan keberanian kecil memberikan peringatan yang jelas.”
Bhumi dan yang lainnya pun tersenyum. Mereka menyadari Ramadhan merupakan bulan revolusi batin mulai dari lapar lahir empati hingga dari empati lahir keberanian.
Mereka kembali bertugas dan patroli, suasana Kota tetap sibuk dan Baleho tetap berdiri. Namun di dalam hati mereka, ada api kecil yang terus menyala.
Malam bulan Puasa tahun ini terasa lebih dalam, Karena mereka tidak hanya menahan lapar, menahan kecewa, menahan amarah dan Menahan rasa tidak adil, Di antara doa-doa yang lirih, terucap satu harapan, “Ya Allah, jadikan kami aparat yang sabar, tapi jangan jadikan kami alat bagi ketidakadilan yang di ciptakan para pemimpin kami.”
Di Kota Industri yang benderang oleh lampu-lampu jalan serta Lampu-lampu pabrik, mereka terus berjalan dalam kegelapan yang sunyi, mencari cahaya keadilan dan kesejahteraan, karena di bulan Ramadhan seharusnya para pemangku kekuasaan menyucikan pula kebijakan.
Epilog : Teologi Lapar
Suasana Kota Industri di malam awal Ramadhan terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu jalan tetap menyala dan Baleho dengan slogan besar tetap berdiri. Sedangkan Target kegiatan rutin tetap terus berjalan Tetapi di dalam dada para aparat petugas lapangan, ada ruang yang terus berdialog dengan Tuhan.
Bhumi pernah berkata pelan di antara suara kendaraan dan takbir sholat tarawih, “Lapar itu bukan sekadar kosongnya perut, Lapar merupakan bahasa tubuh ketika keadilan tidak pernah sampai.”
Dan dari sanalah istilah itu menemukan maknanya, Teologi Lapar bukan ajaran tentang mengkultuskan penderitaan, bukan pula pembenaran untuk pasrah pada ketimpangan.
Teologi Lapar adalah kesadaran bahwa, Ketika manusia dipaksa hidup di bawah standar yang ia tegakkan sendiri, Ketika aparat diminta menjaga ketertiban sementara kesejahteraannya diabaikan dan Ketika ibadah dijalankan dalam tekanan ekonomi dan batin, Maka iman tidak boleh diam, karena Teologi Lapar adalah spiritualitas yang lahir dari realitas sosial. Ia berdiri di antara sajadah dan kebijakan anggaran, bergetar di antara doa dan data, lalu mengajarkan bahwa sabar bukan berarti membiarkan kezaliman dan juga mengajarkan bahwa ikhlas bukan berarti menyerah pada ketidakadilan.
Karena Dalam Islam, lapar saat puasa merupakan latihan empati. Akan Tetapi ketika lapar menjadi kondisi struktural akibat kebijakan yang tidak berpihak, maka ia berubah menjadi pertanyaan teologis, Di mana keadilan itu ditempatkan dalam tata kelola kekuasaan?, Apakah amanah hanya retorika, atau tanggung jawab moral yang nyata?
Al-Ghazali mengingatkan bahwa, “kekuasaan tanpa keadilan merupakan awal kehancuran yang tertunda,” dan Ibnu Khaldun menulis bahwa “kezaliman adalah tanda awal runtuhnya peradaban. Maka Teologi Lapar berdiri sebagai peringatan, ketika aparat negara sendiri hidup dalam ketimpangan, sistem sedang menggerogoti fondasinya.”
Kisah ini tidak berakhir pada kemarahan, Satria Perkasa tetap memimpin pasukannya dan Cak IIP tetap menjalin komunikasi dengan dewan. Kang Ibay tetap merapikan laporan bulanan. Erdan, Defan, Mamat, dan Bhumi terus berpatroli, tetap menjaga ketertiban kota.
Mereka memilih jalan yang lebih sulit, tetap profesional tanpa kehilangan nurani dan Teologi Lapar, pada akhirnya, adalah Keyakinan bahwa keadilan merupakan bagian dari ibadah melalui gerakan dalam memperjuangkan kesejahteraan bukan pemberontakan, tapi tanggung jawab moral.
Iman yang sejati tidak hanya diuji oleh lapar perut, tetapi oleh keberanian menghadapi ketidakadilan, di Kota Industri itu, puasa tetap berjalan dan Doa tetap terangkat.
Kritik tetap disuarakan dengan santun dan mungkin suatu hari nanti, ketika kebijakan berubah dan keadilan menemukan bentuknya dalam angka yang layak, Teologi Lapar tidak lagi menjadi jeritan sunyi, melainkan menjadi saksi bahwa kesabaran dan keberanian pernah berjalan beriringan. Karena pada akhirnya, Lapar boleh datang setiap Ramadhan, Tetapi ketidakadilan tidak boleh dijadikan takdir yang menciptakan penderitaan panjang.
======BERSAMBUNG======
ARDHI MORSSE, KAMIS 19 FEBRUARI 2026